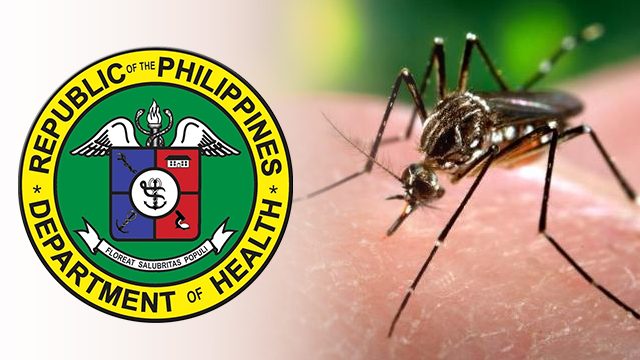Radikalisme atau LGBT, Ancaman Mana yang Lebih Serius?
keren989
- 0
Membaca menuju Republika pekan lalu yang bertajuk “LGBT Ancaman Serius” tidak membuat saya yakin bahwa itulah headline surat kabar nasional.
Mengapa LGBT harus menjadi ancaman serius? Seharusnya pertanyaan ini dijawab oleh pemimpin redaksi, namun sayangnya yang bersangkutan tidak siap menjawab.
Lalu saya berpikir, benarkah LGBT menjadi ancaman serius bagi generasi muda? Bagaimana dengan isu lain seperti radikalisme? Mana yang lebih berbahaya?
Jika mengingat hari-hariku di kampus Universitas Airlangga Surabaya, ada satu hal yang menonjol, kerumunan orang yang mengaji di masjid atau musala, selebihnya adalah anak-anak aktivis sayap kiri yang asyik nongkrong di kantin.
Tidak ada salahnya bagi mereka yang mengaji, saya juga bagian dari mereka, mempelajari agama Islam, tidak hanya lahir di keluarga muslim dan terus menjadi muslim, menurut saya itu penting.
Namun dalam perjalanan saya mempelajari Islam di kampus, saya menemukan banyak ‘mazhab’, sudah bukan rahasia lagi, mulai dari yang moderat hingga konservatif.
Namun seperti yang dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saya sama sekali tidak khawatir dengan konservatisme dalam beragama. Saya sependapat dengan Lukman, konservatisme yang kini bergeser maknanya menjadi radikal, bagus kalau diartikan radikalisasi, tapi kalau dibarengi dengan kekerasan, lain halnya.
Ketika saya pelajari, ternyata mereka tidak hanya mengajarkan agama Islam, tapi juga negara-negara Islam. Saya kira ketika saya masih kuliah awal, belum ada warga yang berpikir untuk mendirikan negara Islam karena penganut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hidup berdampingan di desa saya.
Saya juga berpendapat bahwa tidak ada orang seperti Jemaah Islamiyah dan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang akan mengangkat senjata karena ada gerakan pemuda Islam yang mendirikan Partai Keadilan (saat ini Partai Keadilan Sejahtera) yang akan memenuhi keinginan umat Islam untuk mengakomodasi. . untuk menjaga nilai-nilai Islam di kepulauan Indonesia.
Namun entah kenapa tiba-tiba ada seruan dari jemaah lain untuk mempertahankan khilafah Islam di kampus lewat halaqah-halaqah (kelompok pengajian kecil) yang rutin dilakukan di masjid universitas atau musala di masing-masing fakultas.
Jujur saja, jika Anda seorang pelajar dan membaca artikel saya, pasti salah satu dari Anda diminta untuk mengaji. Mula-mula belajar Islam, lalu organisasi, lalu lebih serius lagi manajemen jamaah.
Seruan ini bukan sekadar khayalan, bahkan mereka punya target repelita, seperti Soeharto, rencana pembangunan lima tahun, membangun kampus di wilayah ‘kolonial’ mereka. Dalam lima tahun, misalnya, jemaah A akan menaklukkan kampus Z melalui pembentukan kader.
Hanya jemaah di kampus saja, ternyata setelah itu masih ada tahapan jemaah yaitu berkarir di masyarakat. Bergabunglah dengan mereka nanti di sidang yang lebih serius.
Disaat dunia jemaah yang ingin mendirikan negara Islam sedang serius melakukan kaderisasi, saya juga bergaul dengan teman-teman sesama pecinta sesama jenis. Jumlah mereka sangat-sangat sedikit. Mungkin Anda bisa menghitungnya dengan jari Anda.
Tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang mereka. Mereka hampir hidup soliter. Mereka tidak memiliki rencana respons. Terlepas dari rencana repelita, mereka bahkan menolak mengungkapkan identitas mereka. Dengan alasan malas menghadapi penghinaan dan keluarga besar.
Kalaupun ada gerakan, mereka tetap memperjuangkan seks aman dalam diri mereka. Sebab virus HIV/ADIS bisa menyerang siapa saja, jika tidak melakukan hubungan seks yang aman.
Hingga 14 Januari pagi kemarin, saya berpikir, mungkin gerakan Islam di Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih moderat, seperti misalnya bergabung dengan partai atau gerakan masyarakat yang dipimpin NU dan Muhammadiyah.
Tapi sepertinya bom Thamrin membuka mata saya lebar-lebar, bahwa bom itu masih ada dan bertambah banyak. Benih-benih radikalisme berbalut kekerasan terus tumbuh, dan kini siap dipanen.
Mereka bukanlah orang-orang sakit yang bisa menyebarkan orientasi seksualnya, tidak memperbanyak diri, juga tidak mau melakukan kudeta dengan berteriak-teriak mengatasnamakan Tuhan lalu melemparkan bom ke umat Islam lain yang lewat. Target mereka hanya satu: persamaan hak dengan kaum heteroseksual.
Saya ke Solo dan melihat sendiri bagaimana mereka merekrut teroris melalui tahapan amaliyah yang harus dilakukan. Selengkapnya dapat dibaca di sini.
Lalu seminggu kemudian, tiba-tiba isu Support Group dan Resource Center for Sexuality Studies (SGRC) Universitas Indonesia sebagai klub LGBT menjadi hangat di media massa. Klub ini dianggap sebagai gerakan LGBT di kampus yang terletak di Depok.
Pasalnya, hal tersebut rupanya dibantah oleh salah satu pendirinya sendiri yang bukan seorang LGBT, Nadya Karima Melati. Organisasi ini sebenarnya dinilai sangat bermanfaat, karena di Ask.fm misalnya, mereka menjawab pertanyaan seputar kekerasan dalam hubungan.
Isu LGBT kemudian merebak hingga Front Pembela Islam menyebut empat orang lesbian dianggap meresahkan warga sehingga terpaksa ditangkap. Satu pertanyaan saja dari saya, bagaimana FPI bisa tahu kalau mereka lesbian? Bagaimana jika mereka biseksual atau straight seperti kebanyakan orang?
Perdebatan mengenai LGBT kemudian meluas hingga ke ruang redaksi. Editor surat kabar tertentu secara terbuka mewaspadai LGBT. Saya tidak tahu apa yang mereka waspadai.
Bahkan, kata Dina Astuti, dosen yang pernah mengajar mata kuliah bertajuk Seksualitas Manusia (Seksualitas manusia) di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, jumlah orang yang tergabung dalam kelompok LGBT lebih sedikit dibandingkan heteroseksual. Baca pernyataan Dina halaman Facebook-nya.
Namun kaum LGBT seringkali menerima dan menerima pandangan negatif, prasangka, bahkan diskriminasi dan kebencian dari lingkungan yang tidak memahami seksualitas.
Psikiatri dan Psikologi telah mengecualikan homoseksualitas dari kriteria gangguan jiwa sejak tahun 1973.
Kelompok LGBT adalah orang-orang sehat yang memiliki identitas dan orientasi seksual yang berbeda dengan orang pada umumnya, namun perbedaan tersebut tidak menjadikan mereka sakit, terganggu atau tidak mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif.
Mereka bukanlah orang-orang sakit yang bisa menyebarkan orientasi seksualnya, tidak memperbanyak diri, juga tidak mau melakukan kudeta dengan berteriak-teriak mengatasnamakan Tuhan lalu melemparkan bom ke umat Islam lain yang lewat. Target mereka hanya satu: persamaan hak dengan kaum heteroseksual.
Pertanyaannya adalah, apakah kita menganggap perjuangan mereka tanpa senjata dan persamaan hak sebagai sebuah ancaman?
Mungkin kita perlu bercermin dan menetapkan prioritas. Sebenarnya, apa yang lebih mengancam keamanan nasional, gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara di dalam negara atau pasangan sesama jenis yang memperjuangkan hak-hak pribadinya? —Rappler.com
Febriana Firdaus adalah jurnalis Rappler Indonesia. Ia fokus membahas isu korupsi, HAM, LGBT, dan pekerja migran. Febro, sapaan akrabnya, bisa disebutkan @FebroFirdaus.
BACA JUGA: