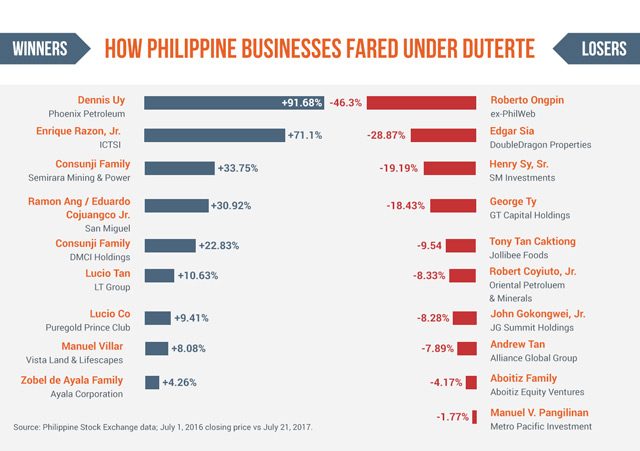Kisah seorang penyandang disabilitas yang berjuang demi pendidikan
keren989
- 0
YOGYAKARTA, Indonesia – Tes wawancara dalam proses lamaran kerja seringkali menjadi tahapan yang paling ditakuti para pencari kerja. Bagi Ida Puji Astuti Maryono Putri, butuh waktu tiga tahun untuk bisa melewati tahap ini dan berhasil mendapatkan pekerjaan.
Alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan pemegang gelar master dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina, ini tak pernah mendapat jawaban pasti mengapa ia tidak berhasil melewati berbagai tahapan tes saat mencari pekerjaan. hingga tiga. bertahun-tahun. Wanita kelahiran Boyolali dengan tinggi badan 110 cm ini mengalami gangguan kesehatan saat masih balita.
Setelah melalui berbagai kendala hidup, Ida akhirnya merintis pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk menutup kesenjangan antara penyandang disabilitas di masyarakat.
“Saat pengurusan surat keterangan di Tangerang, kata salah satu polisi, mesin yang bekerja saja lebih besar dari badan saya.”
“Apapun kondisi fisik saya, selama saya mampu pasti tidak menjadi masalah. “Tetapi dunia ini masih sangat idealis, dan konsep itu tidak terjadi pada saya,” kata Ida kepada Rappler pada pertengahan Juli lalu.
Seorang dokter ortopedi mendeteksi adanya pengapuran pada persendian lengan dan kaki Ida saat ia berusia 10 tahun. Organ tubuhnya tumbuh dan berkembang, namun lengan dan kakinya tidak.
“Sejak saya berumur 3 tahun, orang tua saya tanpa kenal lelah mencari obat untuk penyakit saya dan fokus pada terapi. “Tubuh dan wajah saya berkembang maksimal, meninggalkan kaki dan tangan saya,” akunya.
Beruntung Ida, ia dilahirkan dari orang tua yang sangat menerima kondisinya. Bahkan hingga saat ini, ayahnya selalu ingin membawa Ida kemana pun dia pergi. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di sekolah negeri favorit di Boyolali, sebelum melanjutkan studi di Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2004. Selama itu Ida merasa tidak mengalami diskriminasi karena kondisinya.
“Guru di sekolah memperbolehkan saya untuk tidak mengambil mata pelajaran olah raga, teman-teman saya sangat membantu. “Bahkan penguji saya saat sidang skripsi membantu menata meja dan kursi sedemikian rupa agar sesuai dengan postur tubuh saya dan presentasi bisa maksimal,” ujarnya.
Dunia terasa berbeda setelah Ida menyelesaikan kuliahnya. Anak kedua dari tiga bersaudara ini harus mandiri dan mempunyai pekerjaan dengan gelar sarjana. Pencariannya dimulai di Boyolali, kemudian ia mencari pekerjaan di Jakarta selama dua bulan, namun tidak membuahkan hasil.
“Setelah wawancara pasti tidak akan dipanggil lagi. Saya dua kali mendaftar ke sekolah internasional di Tangerang. Aplikasi pertama berhenti setelah tes bahasa Inggris. “Pendaftaran kedua dengan panitia yang sama bilang mereka kaget kenapa saya tidak dipanggil tes bahasa Inggris lagi karena nilai saya di lamaran sebelumnya lolos,” kenang Ida.
Saat pengurusan surat keterangan di Tangerang, salah satu petugas polisi juga mengatakan, mesin yang bekerja saja lebih besar dari badan saya.
Belajar di Amerika dan dapatkan gelar master
Ida lulus dari universitas pada tahun 2004. Dengan dukungan terus-menerus dari keluarganya, pencarian pekerjaannya mulai membuahkan hasil.
Ia diterima sebagai pengolah data di Lembaga Kajian Transformasi Sosial (LKTS) Solo pada tahun 2007 dan menetap selama lima tahun. Sejak saat itu, sejumlah pekerjaan lain mulai bermunculan, termasuk sebagai kontributor atau penulis lepas. Ida dan timnya sudah terbiasa bepergian dengan angkutan umum untuk memenuhi tenggat waktu penulisan.
Upaya mencari beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri pun membuahkan hasil manis. Dimulai dengan pelatihan singkat di Amerika pada bulan Juli-Agustus 2010 tentang pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas, kemudian menjadi peserta konferensi pariwisata aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada tahun 2014, pelatihan jurnalisme di Australia pada tahun 2015, dan beasiswa untuk gelar master di Politik Global dari Departemen Ilmu Politik di Universitas Ateneo di Manila, Filipina.
Ida berhasil memperoleh gelar masternya dan kembali ke Indonesia pada Juli 2017. Setelah membaca banyak buku, dia tidak pernah takut dengan orang asing dan petualangan di negara lain.
“Yang sulit adalah meyakinkan orang tua saya bahwa saya akan berhasil di luar negeri. “Saya sendiri tidak takut, karena sejak sekolah saya sering membaca buku terjemahan dan saya tahu banyak tentang Amerika dan tempat lain,” ujarnya.
Jabatan baru sebagai project officer di Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) di Yogyakarta disambut baik dan dimulai pada pertengahan Juli 2017.
Pendidikan untuk semua
Selain bekerja, Ida juga merintis PAUD di Desa Ringinlarik, Kecamatan Muso, Boyolali, sejak tahun 2015. PAUD didirikan untuk mengikis kesenjangan segregasi yang tercipta antara masyarakat dan penyandang disabilitas. Ia berupaya mewujudkan pendidikan yang memberikan fasilitas kepada peserta didik penyandang disabilitas, sekaligus memiliki sistem yang tidak mengabaikan penyandang disabilitas, serta mampu membangun jembatan pemahaman antara penyandang disabilitas dan masyarakat.
Ia mengatakan hal itu dimulai dari peningkatan pemahaman untuk menghapuskan diskriminasi dan meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dari dalam keluarga.
“Penyandang disabilitas adalah manusia. Pengguna kursi roda yang satu tidak bisa disamakan dengan pengguna kursi roda lainnya. Mereka juga memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda.”
“Penyandang disabilitas adalah manusia. Pengguna kursi roda yang satu tidak bisa disamakan dengan pengguna kursi roda lainnya. Mereka juga mempunyai potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. “Keluarga dan lingkungan berperan besar dalam memberikan rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
PAUD berjalan dibantu rekan penyandang disabilitas lainnya, Titik Isnaini.
Ida mengaku beruntung tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung dan sekolah yang tidak membeda-bedakan kondisinya. Saat ia masih menjadi pelajar, pihak sekolah hanya memandang Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai indikator diterima atau tidaknya, tanpa melihat kondisi fisiknya.
Namun sistemnya telah berubah dan kini pendidikan dituntut menjadi sekolah inklusif yang memberikan sarana dan fasilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus (SEN). Menurutnya, penyandang disabilitas dan masyarakat memerlukan ruang yang sama untuk berbaur, agar penyandang disabilitas semakin percaya diri dan masyarakat juga memandang penyandang disabilitas sebagai anggota komunitas yang sama.
“Seperti halnya perundungan terhadap mahasiswa autis di Universitas Gunadarma, lingkungan pendidikan mungkin sudah mempunyai fasilitas, tapi sistem pendidikannya belum. “Ada jarak antara siswa difabel dengan yang lain,” kata Ida.
“Di lapangan, saya mendengar dari teman-teman difabel lain bahwa kondisinya sangat mirip. Situasinya tidak sesederhana itu. Bagaimana menciptakan sistem yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, dengan memanusiakan manusia.” —Rappler.com