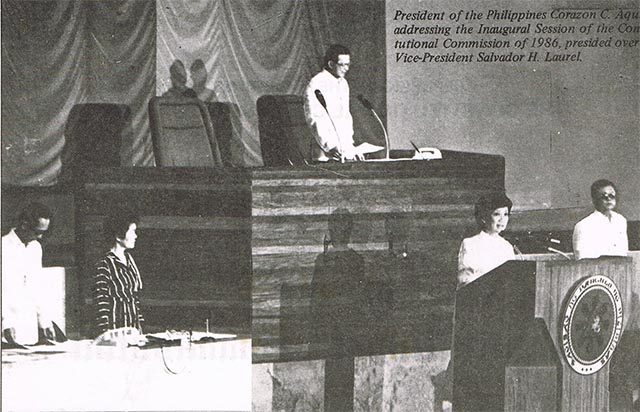LGBT di Indonesia: Bukan Warga Negara Kelas Dua
keren989
- 0
Harapan kelompok LGBTIQ di Indonesia sederhana saja, mereka hanya ingin diperlakukan setara dan tanpa diskriminasi
“Sudah gay?”
Bagi pria yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, pertanyaan-pertanyaan di atas adalah hal yang wajar untuk ditanyakan, baik dalam konteks bercanda maupun dengan tujuan yang menyinggung.
Lucunya setiap hari kita dihadapkan pada program-program yang menyentuh atau bahkan mengeksploitasi masalah ini. Media ibarat mata uang yang memiliki dua sisi, ketika ada pemberitaan yang menyasar kelompok LGBT, maka orang-orang tersebut diberitakan secara intensif tanpa jeda.
Namun di sisi lain, media juga menjadikan tokoh atau isu LGBTIQ sebagai bumbu dan pelengkap acara komedi, sinetron, atau hiburan di media. Acara bincang-bincang yang ditonton oleh berbagai kalangan dan usia. Masyarakat Indonesia memahami bahwa persoalan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, suka atau tidak, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh agama.
Homoseksualitas yang merujuk pada orientasi seksual terhadap sesama jenis sebenarnya merupakan salah satu spektrum dari isu yang jauh lebih besar yaitu LGBTIQ atau dalam bahasa Inggris lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks dan interogasi.
Sebagai orang awam dan bukan psikolog atau aktivis LGBTIQ di Indonesia, saya merasa isu ini selalu dilontarkan dan dibicarakan dari tahun ke tahun, tanpa pernah ada “kesepakatan” yang jelas di masyarakat.
Isu LGBTQ merupakan isu musiman yang selalu dibicarakan ketika ada peristiwa yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya saja legalisasi pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian Amerika Serikat pada tahun lalu.
Awal tahun ini, isu ini ramai dibicarakan karena sekelompok mahasiswa sebuah universitas memberi tahu publik tentang adanya hal tersebut grup pendukung bagi remaja putra dan putri yang menginginkannya keluar dari lemari atau membuka diri kepada masyarakat bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas LGBTIQ.
Yang saya maksud dengan “kesamaan” adalah mengubah persepsi dan pola pikir masyarakat bahwa persoalan LGBTIQ bukan hanya persoalan seks dan kesukaan terhadap sesama jenis. Masih banyak hal yang lebih penting untuk dibahas, yaitu persamaan kesempatan untuk diperlakukan sama dalam masyarakat, tanpa pembedaan dan berdasarkan keadilan.
Yang dibicarakan selama ini hanya dalam koridor agama atau “adat istiadat oriental” atau dalam pandangan kaum heteroseksual bahwa pasangan harus laki-laki dan perempuan, itulah yang dianggap normal atau “tidak sakit” sehingga timbullah diskriminasi bagi mereka yang tidak selaras dan harmonis. .
Akibatnya, kelompok LGBTIQ menjadi warga kelas dua karena alasan sederhana, yaitu hidup yang “dikutuk” agama.
Selanjutnya ketika saya duduk di bangku SMA, pada pelajaran Antropologi, saya memahami bahwa salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang munafik, istilah yang lebih halus dari kata “munafik”. Apakah itu benar? Mungkin ada benarnya juga.
Saya melihat kita cenderung menggunakan standar ganda dalam segala situasi. Kita cepat menilai namun lambat mengevaluasi. Kita sepertinya baik-baik saja dan tidak begitu emosional terhadap isu pekerja seks komersial, pornografi di media massa dan film, perceraian atau korupsi. Tampaknya ada tingkat kemarahan dan penilaian yang berbeda ketika dihadapkan pada isu LGBTIQ.
Saya melihat harapan kelompok LGBTIQ di Indonesia sederhana saja, mereka hanya ingin diperlakukan setara dan tanpa diskriminasi. Mereka tidak dipaksa menjadi heteroseksual, tidak dipaksa menikah atau dibawa ke pusat rehabilitasi keagamaan untuk diubah menjadi lawan jenis.
Memang butuh waktu untuk mengizinkan mereka menikah secara sah di Indonesia, namun penerimaan masyarakat merupakan tahap awal yang diharapkan bisa terwujud secara perlahan. Kita mungkin perlu belajar untuk menjadi bagian dan membentuk masyarakat yang inklusif namun tidak eksklusif.
Saya bisa dibilang beruntung karena saya berada di lingkungan yang berpikiran terbuka, bahwa seseorang dinilai bukan berdasarkan orientasi seksualnya, tapi berdasarkan cara mereka memperlakukan satu sama lain.
Namun banyak juga rekan-rekan di luar sana yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena dibatasi oleh penilaian keluarga, masyarakat atau bahkan teman dekat.
Saya percaya setiap orang boleh saja mempunyai keyakinan dan keyakinannya masing-masing, namun bukan berarti memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang dianutnya. Bukankah setiap orang punya caranya masing-masing?
Salah satu teman saya mengatakan dalam status Facebooknya: “Kita semua mempunyai dosa masing-masing. Ada baiknya kita mulai berhenti merayakan dosa orang lain dan memperbaiki dosa kita sendiri.” —Rappler.com
Lewi Aga Basoeki adalah lulusan hukum yang saat ini bekerja sebagai pengacara perusahaan di sebuah firma hukum terkemuka di Jakarta. Ia tertarik dengan permasalahan hukum terkait isu sosial, LGBT dan masyarakat perkotaan pada umumnya. Ikuti Twitter-nya @Legabas
BACA JUGA: