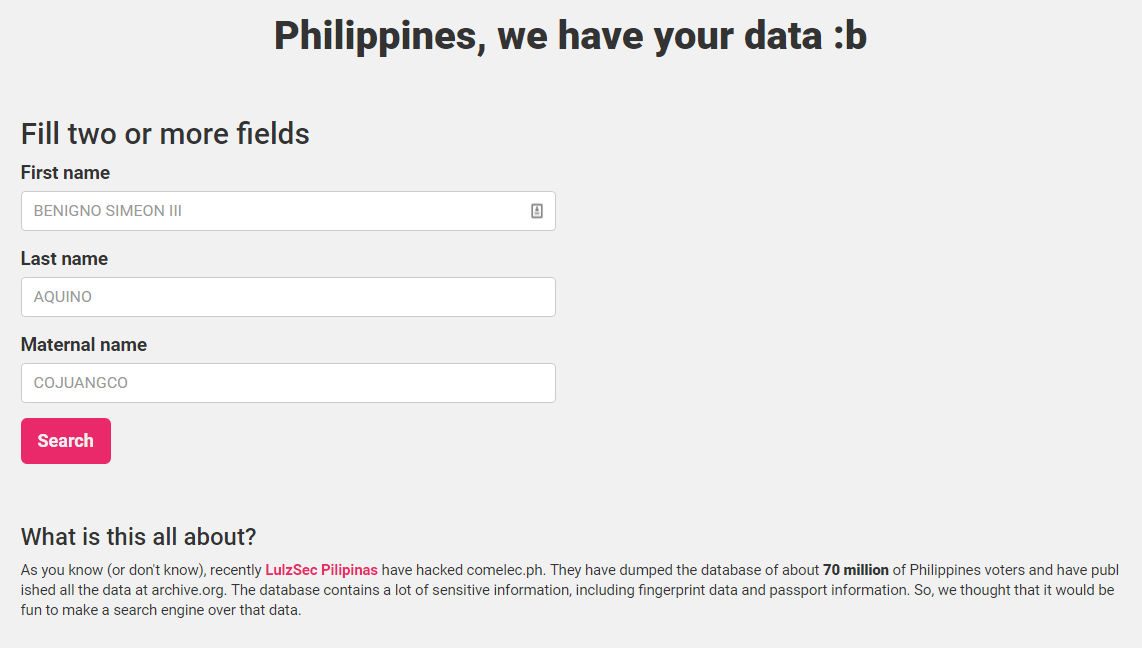Hukuman cambuk di Aceh: Salah pemerintah atau korban?
keren989
- 0
Saat pertama kali hukuman cambuk dijatuhkan kepada RS, seorang perempuan beragama Kristen di Aceh, masyarakat baik dalam perbincangan sehari-hari, diskusi melalui media sosial, maupun melalui media massa mengutarakan beberapa pendapat berbeda.
Setidaknya ada tiga kelompok besar pendapat yang dapat dicermati. Yang pertama adalah mereka yang menyalahkan pemerintah Aceh karena menerapkan undang-undang yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Kedua, mereka menyalahkan pemerintah pusat yang mengabaikan pelanggaran HAM di sana.
Yang ketiga, dan tidak sering disebutkan, adalah menyalahkan “korban” karena dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan budaya setempat.
Reaksi pertama saya, seperti kebanyakan orang yang menaruh perhatian pada hak asasi manusia, adalah menyalahkan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat atas 28 pembunuhan RS pada Selasa, 12 April.
“Jokowi diam,” kata Pendeta Domidoyo Ratupenu, aktivis keberagaman yang sudah beberapa tahun tinggal di Aceh, kepada saya, Minggu, 16 April.
“Jika pemerintah pusat secara tegas menyatakan penerapan Qanun Jinayat merupakan pelanggaran konstitusi, maka saya yakin kelompok Islam seperti NU akan mendukung pemerintah,” ujarnya.
Saya setuju. Pemerintah memang bungkam. Dan bisa jadi itu adalah salah satu dari beberapa hal yang diduga menjadi penyebab masalah tersebut. Selain residensi, kendali pemerintah terhadap peraturan daerah di Aceh tidak kasat mata, apalagi tidak ada.
Jadi selain pemerintah pusat, apakah patut menyalahkan pemerintah Aceh? Bukankah mereka mempunyai hak untuk menetapkan aturan yang mereka anggap baik?
Dalam persepsi aktivis hak asasi manusia, hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman fisik merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam pandangan sebagian pengambil aturan di sana, keputusan tersebut mungkin terkait dengan keinginan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak ada yang menirunya.
Apa itu bekerja? Jawabannya adalah tidak. Pelanggaran masih ada. Namun saya tidak berwenang menilainya dari segi hukum.
Sementara itu, mereka yang menyalahkan RS – seorang perempuan berusia 60 tahun yang dihukum karena menjual minuman keras – mengatakan bahwa hukuman cambuk kurang lebih tepat karena ia telah melanggar peraturan setempat.
Dimana bumi dipijak, disitulah langit dipelihara.
Jadi salah siapa ini?
Dari sudut pandang komunikasi, hal ini dapat dilihat dari dua aspek: komunikasi antar budaya dan teori spiral perumahan. Saya tidak ingin membahas hak asasi manusia atau hukum Islam karena walaupun penting, hal ini bukanlah bidang keahlian saya dan sudah sering saya bahas.
RS yang menelusuri asal usul nama belakangnya dari Sumatera Utara sepertinya gagal beradaptasi dengan budaya setempat. Dalam syariat Islam yang diterapkan di Aceh, minuman beralkohol jelas dilarang.
“Jika Anda dan banyak umat Islam lainnya tidak setuju, mengapa Anda diam saja? Tempat tinggal ini seperti bentuk persetujuan atas tindakan mereka.”
“Ada lapo di belakang gereja saya. “Dan memang banyak dari etnis tersebut yang berjualan minuman keras,” kata Pendeta Domi.
Penduduk Sumatera Utara dan Aceh yang letaknya berdekatan kemungkinan besar akan saling bersentuhan. Konflik antara dua budaya yang berbeda dapat dengan mudah terjadi apabila masing-masing tidak memahami cara komunikasi antar budaya yang baik.
Jadi siapa yang harus beradaptasi dengan budaya siapa? Terlepas dari etnisitas dalam kasus RS, pendatang selalu diharapkan untuk beradaptasi dengan budaya tuan rumah, termasuk ketaatan pada aturan budaya setempat.
Lalu bagaimana jika aturan budaya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang? Satu-satunya pilihan baginya adalah beradaptasi, ia meminta budaya tuan rumah untuk beradaptasi atau menolak pergi ke sana, dalam artian tidak pergi ke tempat itu.
Jika pilihan yang diambil adalah pergi ke suatu daerah dengan budaya yang berbeda, maka cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan beradaptasi dengan budaya tuan rumah. Tidak mungkin meminta semua anggota suatu budaya, termasuk otoritas budaya, untuk memahami seseorang yang berbeda. Dalam hal ini, rumah sakit tidak boleh menjual minuman keras. Lagipula, dengan tidak menjual minuman keras, tidak bertentangan dengan budaya.
Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun terdapat “kesalahan lintas budaya” yang dilakukan RS, hal ini tidak berarti bahwa saya menyetujui hukuman cambuk.
Spiral perumahan
Dalam sebuah diskusi, seorang teman media tempat saya bekerja menyatakan kesal dengan kelakuan Front Pembela Islam (FPI) garis keras. Saya akhirnya menyuarakan apa yang ada di pikiran saya selama beberapa tahun.
“Jika Anda dan banyak umat Islam lainnya tidak setuju, mengapa Anda diam saja? “Tempat tinggal ini seperti bentuk persetujuan atas tindakan mereka,” kataku.
Jawabannya: “Kalau saya ngomong seperti di media sosial, pasti ada orangnya langsung hakim “Kamu bukan Muslim, kan?” Itu membuatku malas berkomentar.”
Banyak teman-teman Muslim saya yang tidak menyukai kelompok fanatik yang berpikiran sama. Mereka enggan mengutarakan pendapatnya karena khawatir akan disalahartikan. Namun, ada juga yang aktif menyatakan ketidaksetujuannya. Sayangnya, suara mereka yang memilih mengutarakan pendapatnya tidak sekeras suara kelompok fanatik tersebut.
Jumlah kelompok intoleran tidak banyak. Namun aksi ekstrem yang kerap mereka lakukan mendapat tempat yang relatif besar di media sehingga terkesan besar.
Lalu apakah diam merupakan sikap yang benar? Tidak jika kamu menurut Teori Spiral Keheninganatau Teori Tempat Tinggal.
Menurut teori yang diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Elisabeth Noelle-Neumann dari Jerman, orang yang percaya bahwa posisi mereka dalam suatu isu tertentu adalah posisi minoritas akan menyimpannya di “latar belakang”. Ini menghalangi komunikasi mereka dengan luar. Sebaliknya, mereka yang yakin bahwa posisinya adalah posisi mayoritas akan lebih termotivasi untuk bersuara.
Akibatnya, suara minoritas akan semakin tenggelam seiring dengan semakin menguatnya suara mayoritas. Jika hal ini dibiarkan, suara minoritas akan hilang.
Lalu bagaimana cara mengakhiri masalah ini?
Kembali ke sudut pandang komunikasi antarbudaya, RS dan kita semua harus belajar menghargai budaya tempat kita berkunjung atau singgah dalam waktu tertentu. Hal ini berguna untuk menghindari konflik yang tidak perlu.
Kedua, bagi orang atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap hal ini, kepedulian saja tidak cukup. Kekhawatiran jika ditempatkan pada teori spiral perumahan ini akan hilang jika tidak disikapi dengan strategi yang tepat.
Bentuknya tentu saja bukan seruan individual yang juga akan hilang di tengah kebisingan, melainkan membentuk upaya kolektif untuk mengungkapkannya. Upaya kolektif, dengan atau tanpa kelompok atau individu yang berpengaruh, dapat digunakan untuk mendorong para pemegang kekuasaan, baik di daerah maupun pusat, untuk mengambil sikap yang benar.
Ketiga, upaya mencegah hilangnya suara minoritas dapat dilakukan melalui media. Dalam sebuah diskusi terkait intoleransi, seorang pemimpin redaksi media di Indonesia pernah mengatakan bahwa tidak perlu ada keseimbangan dalam meliput isu intoleransi. Masyarakat yang mengusung semangat intoleransi tidak perlu diberi wadah di media. Tujuannya adalah untuk menghentikan suara mereka agar tidak semakin keras.
Pada saat yang sama, media harus memberikan tempat bagi kelompok minoritas untuk menyampaikan pandangannya dan bagi mereka yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap kelompok intoleran. —Rappler.com
Camelia Pasandaran merupakan mantan jurnalis media cetak dan online. Beliau merupakan dosen komunikasi antar budaya dan jurnalisme di Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
BACA JUGA: