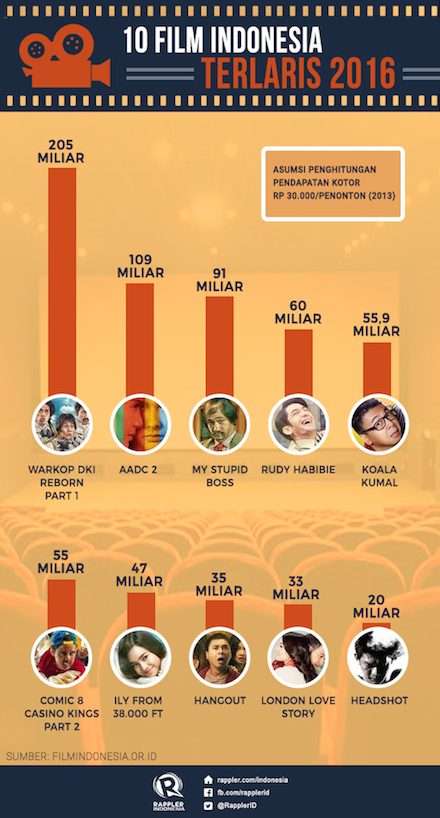Memahami rasisme anti-Tionghoa di Indonesia
keren989
- 0
JAKARTA, Indonesia – Rasisme merupakan masalah universal yang menimpa seluruh negara di dunia. Indonesia pun tidak lepas dari permasalahan ini, khususnya bagi warga keturunan Tionghoa.
Kasus dugaan penodaan agama terkait Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama membuat sentimen anti-Tionghoa kembali digaungkan secara luas. Tindakan pejabat keturunan Tionghoa tersebut seolah menjadi media kaum rasis untuk menyalurkan kebenciannya.
Namun Direktur Eksekutif dan Peneliti Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, kelompok rasis ini sebenarnya kecil.
“Selama 15 tahun, intoleransi terhadap etnis Tionghoa kecil, hanya sekitar 0,8 persen dengan margin of error 3 persen,” kata Saiful dalam diskusi “Ada Apa di Balik Sentimen Anti-Tionghoa?” pada Kamis, 29 Desember, di Jakarta.
Hasil tersebut ia peroleh dari penelitian pada tahun 2001 hingga 2016. Berdasarkan survei, kelompok yang paling dibenci adalah Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS); diikuti oleh warga lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT); Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sisanya terbagi rata antara Yahudi, Wahhabi, dan etnis Tionghoa.
Karena itu, Saiful menilai kebencian terhadap warga keturunan Tionghoa bukanlah sesuatu yang masif. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang terus berupaya menghasut isu ini.
Hal ini terlihat dari kasus Ahok. Faktor pertama, gerakan sosial anti China muncul ketika kelompok tertentu melihat pejabat yang berkuasa tidak sesuai harapan sehingga harus mengerahkan massa untuk membentuk opini buruk.
Selanjutnya, kelompok yang sama mengerahkan massa untuk melakukan perlawanan. Terakhir, ajaran dan pendapat kolektif disebarluaskan kepada warga turunan.
“Ada ide, semangat, sentimen, jargon, ajaran, doktrin yang memberi makna dan menarik masyarakat untuk membentuk solidaritas kolektif bahkan membentuk semacam identitas sosial baru,” kata Saiful.
Dalam dunia politik, penggunaan isu rasial merupakan hal yang sangat lumrah. Misalnya saja pada pemilu dari Amerika Serikat hingga Prancis.
Dalam kasus Ahok, motif serupa juga terjadi. “FPI cs. Siapa yang membawa minoritas ganda dibingkai dan dugaan penodaan agama Islam, teman-temannya semakin meningkat ketika kontestasi politik nyata terjadi di DKI,” kata Saiful.
FPI, lanjutnya, tidak menyukai Ahok sejak ia mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Namun, saat itu protes mereka kecil-kecilan dan tidak terdengar.
Kali ini berbeda. Saingan Ahok dan pendukungnya di Pilkada DKI kerangka itu menjadi lebih besar. Bagi mereka, bukan lagi soal penodaan agama, tapi bagaimana cara mengalahkan Ahok.
Jadi bukan massa, tapi kelompok tertentu dan diakomodasi oleh media, kata Saiful. Oleh karena itu, ia menyimpulkan, meningkatnya sikap anti-Tionghoa yang terjadi belakangan ini bukanlah cerminan seluruh masyarakat Indonesia.
Konstruksi bersejarah
Sentimen rasial terhadap warga keturunan Tionghoa bukanlah cerita baru. Sejak masa penjajahan Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, kasus intoleransi terus berulang.
Thung Ju Lan, pakar Studi Tionghoa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan bentrokan antara pribumi dan Tionghoa sudah berlangsung lama. Menyebutnya sejak tahun 1926.
Dalam pasal 163 Konstitusi India (IS), orang Tionghoa disebut sebagai warga negara kelas 2, bersama dengan orang Timur asing. Sementara itu warga warga asli atau penduduk asli masuk sebagai warga kelas 3.
“Ada proses pengecilan sejarah yang justru menunjukkan sisi negatif masyarakat keturunan Tionghoa,” kata Ju Lan. Perbedaan kelas misalnya, tampaknya berasal dari pemerintahan kolonial Belanda yang terkesan eksklusivitas dan superioritas.
Belum lagi klaim tanpa data statistik bahwa orang keturunan Tionghoa kaya dan mendominasi perekonomian Indonesia. “Ada yang menyebutkan 75 persen pada masa Orde Baru, namun belum dijelaskan berapa sebenarnya total aset Indonesia,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Ju Lan, ada juga warga miskin keturunan Tionghoa, seperti Tionghoa Singkawang dan Tionghoa Benteng.
Konflik antara pribumi dan keturunan sering terjadi antar kelas, seperti kelas bawah dan kelas menengah. Namun, umumnya terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah.
“Ada kelas menengah yang masih belum mapan dan rentan terjerumus ke bawah garis kemiskinan,” ujarnya. Dengan kondisi seperti ini, tidak jarang muncul rasa iri melihat keturunan yang hidupnya mungkin lebih sukses dan mapan.
Masyarakat menganggap warga yang mengungsi ini “mencuri” atau “mengambil” tanah mereka. “Dari sini menular ke warga lain, padahal dasarnya ya hanya kebencian antar golongan,” kata Ju Lan.
Provokasi berita palsu
Gerakan massa dan konflik antarkelas yang mendalam tentunya tidak akan meningkat tanpa adanya berita palsu. Peneliti senior Lembaga Pengkajian Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto memaparkan observasinya terhadap isu “10 juta TKA Tiongkok”.
Sebenarnya ini adalah twist dari pemberitaan Kemenpar yang menyasar wisatawan mancanegara, kata Ignatius. Sebelumnya, Kementerian Pariwisata menargetkan 10 juta wisatawan asal Tiongkok pada tahun 2020.
Namun melalui situs berita palsu, sosok tersebut dikonsep sebagai tenaga kerja asing. Biasanya, kata dia, pemberitaan seperti ini disertai dengan judul-judul yang provokatif dan mengejutkan.
Penjelasan Ignatius mengenai pemberitaan media bbtp. “Artikel opini. Atau tweet/klon yang tidak sah.” @RapplerID pic.twitter.com/NZQUHpSwQb
— Ursula Florene Sonja (@kuchuls) 29 Desember 2016
“Artikel tersebut sebenarnya berupa opini atau sumbernya tidak kredibel,” kata Ignatius. Misalnya saja dari ramainya tweet di media sosial hingga plagiat tulisan dari media lain.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh langsung percaya dan ikut menyebarkan berita bohong seperti ini. Salah satu caranya adalah dengan konfirmasi ke media yang kredibel.
“Kalau tidak ada media lain yang menulis, berarti berita tersebut belum tentu benar,” ujarnya.
Pendidikan besar-besaran
Selain mencegah penyebaran berita bohong, Ju Lan melihat pentingnya pendidikan toleransi. “Kalau memilih tenaga pengajar, harus kompeten. “Tidak memahami konteks, sejarah, dan membantu menyebarkan kebencian,” ujarnya.
Tindakan serupa juga harus diterapkan pada pejabat politik. Sebagai public figure, sikapnya akan ditiru oleh masyarakat.
Untuk memperkuat upaya meredam kebencian tersebut, Saiful menilai perlu ada kebijakan yang komprehensif. Misalnya Presiden ke-4 RI Abdurrahman “Gus Dur” Wahid yang melanggar aturan diskriminatif dalam Inpres no. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.
Kemudian Gus Dur juga menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur yang tentunya menjadi batu loncatan yang luar biasa untuk menghilangkan diskriminasi.
“Solusi terhadap intoleransi bukan dengan meminta masyarakat yang toleran, namun yang paling sistematis adalah dengan memperbaiki hukum dan penegakan hukum,” katanya. Polisi dan pihak berwenang harus bertindak tegas terhadap kelompok intoleran, dengan dukungan konstitusi.
Sebab permasalahan intoleransi bukan hanya sekedar sentimen sosial, namun lebih merupakan permasalahan elite yang mempunyai motif politik dibaliknya.—Rappler.com