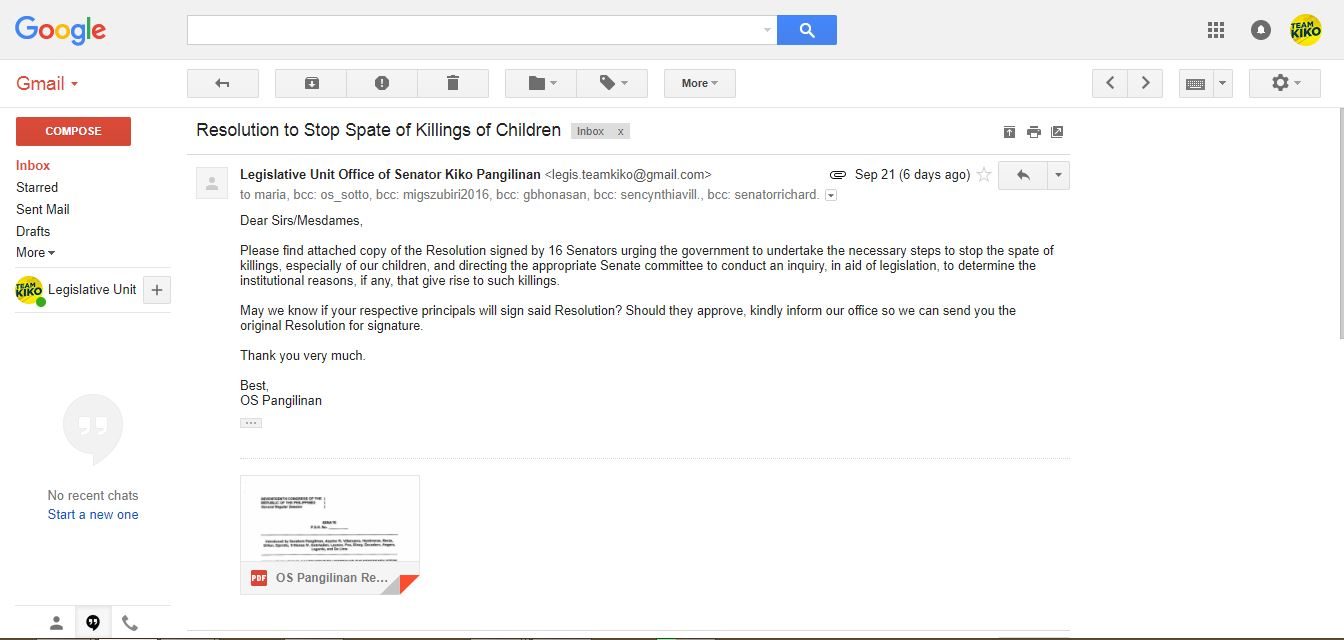Penderitaan mantan tapol yang salah ditangkap dalam tragedi 1965
keren989
- 0
SOLO, Indonesia – Soegianto merupakan anggota TNI AU dengan pangkat Kopral Satu. Sehari-harinya ia bertugas menjaga radar penerbangan militer di Pangkalan Udara Panasan—kini Adi Soemarmo. Setelah peristiwa 30 September 1965 pecah, ia ditugaskan menjaga Kamp Sasono Mulyo, kawasan Keraton Surakarta yang dijadikan tempat penahanan para tersangka anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Namun, tiga tahun kemudian dia tiba-tiba menjadi tahanan. Saat sedang mengerjakan instalasi listrik untuk peralatan radar, ia didekati oleh satuan Polisi AU dan dibawa pergi. Soegianto kaget setengah mati karena ditangkap dengan tuduhan masuk dalam klasifikasi B dalam daftar orang-orang yang terlibat gerakan kudeta ’65.
Soegianto mengalami penyiksaan fisik, mulai dari dipukul dengan tongkat bambu, diremuk hingga kakinya diremukkan oleh kaki kursi jati yang diduduki interogator, sedangkan kedua jarinya disetrum dengan kabel yang disambungkan ke kabel buatan Rusia tersebut. mesin telepon memutar.
Meski penyiksaannya sangat menyakitkan, namun ia tidak mengakuinya karena merasa tidak terlibat dalam gerakan politik apa pun. Ia hanya memahami teknik yang berkaitan dengan radar penerbangan.
“Saya jawab, saya tentara, bukan orang politik, dan tidak tahu apa-apa tentang gerakan kudeta September. Tapi mereka tidak suka dengan jawaban saya, pangkat saya dicopot,” kenang Soegianto, yang kini berusia 74 tahun.
Hari-hari berikutnya ia menjalani masa tahanan, mulai dari Rutan Polsek AU, Rutan Surakarta, hingga tahanan di Mapolres. Ia juga bekerja sebagai teknisi dan terkadang diperintahkan mengemudikan mobil untuk mengangkut tahanan politik.
Selama hampir sebelas tahun Soegianto menjadi tahanan dan kehilangan karier militer serta masa depannya. Ia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1978 di Semarang. Ia dan narapidana lain yang dibebaskan mendapat surat pembebasan yang menyatakan tidak ada bukti keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September 65.
“Setelah hampir sebelas tahun terbukti tidak bersalah, dia baru saja dibebaskan. Faktanya, kami masih harus melapor ke Koramil selama tiga bulan lagi, kata Soegianto.
Namun, dia tidak menyimpan dendam atas kesalahan penangkapan yang menimpanya. Dengan penuh belas kasihan, ia memaafkan seniornya – yang sebelumnya telah menyiksanya – yang kemudian datang secara pribadi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
Kejadian serupa juga dialami Maridi, warga Sukoharjo yang menghabiskan masa mudanya sebagai tahanan politik selama lebih dari 13 tahun, mulai dari kerja paksa hingga pengasingan.
Ia masih remaja berusia 18 tahun saat tragedi itu terjadi. Maridi adalah seorang anak desa yang tidak tahu apa-apa tentang kudeta dan penculikan para jenderal, tapi dia juga ditangkap. Seperti kebanyakan warga kota, ia terkadang ikut menyaksikan keramaian di kotanya – acara seni yang diadakan oleh Pemuda Rakyat.
Sayangnya, beberapa hari setelah kejadian tanggal 30 September 1965, ia didekati oleh gabungan massa anti-komunis dan tentara dan kemudian dibawa ke balai kota. Dia mempertanyakan penangkapannya tetapi diberitahu untuk tetap diam dan tidak berbicara.
“Jika Anda berbicara, Anda dipukuli dan ditendang. “Kami ditahan di tengah jalan dan juga dipukuli,” kata kakek berusia 70 tahun itu.
Ia ditahan dari satu kamp ke kamp lain di kawasan Sukoharjo sebelum dipindahkan ke Kartasura pada November 1965. Bersama narapidana lainnya, ia dipekerjakan di kompleks Kandang Menjangan Kopassus.
Setelah itu, Maridi kembali dipindahkan ke proyek pembangunan Waduk Mulur di Sukoharjo. Setelah menjalani kerja paksa, ia bersama 300 orang asal Sukoharjo dikirim ke Nusakambangan pada September 1968.
Maridi mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan oleh narapidana pidana dan sipir penjara selama 70 hari sebelum akhirnya dipindahkan kembali ke Pulau Buru untuk menjalani masa tahanan yang lebih lama. Di pulau tersebut ia harus bertahan hidup dengan berburu dan meramu karena tidak ada makanan.
“Kami baru bisa menanami sawah baru setelah enam bulan, kami makan apa saja yang bisa kami tangkap. “Buat perangkap binatang, kadang babi hutan, buaya, rusa, tangkap ikan, cari umbi-umbian,” ujarnya.
Di Pulau Buru ia menghabiskan sebelas tahun penjara sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1979. Setelah dibebaskan, ia tetap menjalani wajib lapor ke Koramil selama tiga bulan.
Kehidupannya tidak bisa kembali normal karena Maridi mengalami diskriminasi di desanya sendiri, juga dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ia tidak leluasa menerima surat dari luar karena semua surat yang ditujukan kepadanya harus ditujukan ke kecamatan setempat dan diperiksa terlebih dahulu oleh aparat desa sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia ingin membuka praktik terapi pijat akupresur setelah mendapat rekomendasi dari dokter di puskesmas tersebut. Namun, Maridi tidak bisa mengajukan izin praktik dengan KTP bertanda ET (ex-tapol) karena tidak mendapatkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (CCC) yang dipersyaratkan dari kepolisian dan Koramil.
Hingga saat ini, ia tetap melayani terapi di rumahnya hanya dengan menggunakan sertifikat kursus akupresur tingkat ahli selama tiga tahun.
Mantan tahanan politik di masyarakat
Usai bebas, Soegianto memilih memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya ke depan, terutama menghidupi istri dan anak-anaknya. Lebih penting lagi, bagaimana ia harus bertahan hidup di tengah masyarakat dengan status mantan tahanan politik, sebuah stigma yang melekat pada setiap 65 orang penyintas meski banyak di antara mereka yang belum terbukti bersalah.
Soegianto beruntung karena tidak dikucilkan masyarakat karena statusnya sebagai mantan tahanan politik pada tahun ’65. Bahkan, ia dipercaya menjabat Ketua RT selama 2 tahun dengan dukungan suara terbanyak.
“Mereka tahu, satu desa juga tahu, kalau saya mantan tapol, tapi mereka tidak menghiraukan, dan mendorong saya untuk mencalonkan,” kata Soegianto.
Padahal, sejak masa Orde Baru, ada aturan yang melarang mantan tapol ’65 menduduki jabatan publik di tingkat desa, dusun, dan desa. Namun di kawasan Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, tempat tinggal Soegianto, aturan tersebut tidak berlaku.
Masyarakat di kota tersebut meyakini bahwa Soegianto, mantan anggota TNI, menjadi korban penangkapan di luar hukum dan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September.
Sebaliknya, bagi Maridi, kehidupannya di masyarakat tidak semudah teman-temannya. Tetangga disekitarnya masih sering mencurigainya jika ada tamu atau orang yang datang kepadanya. Tetangganya selalu berprasangka buruk bahwa mantan tapol masih berbahaya.
Ia merasa dikucilkan oleh masyarakat desa karena statusnya sebagai “alumni” Nusakambangan dan Pulau Buru, pulau penjara yang dikenal paling angker karena dihuni oleh penjahat serius dan tahanan politik komunis yang digambarkan brutal.
“Pasien saya semuanya dari luar kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak ada satu pun warga sekitar kota yang mengetahui status saya,” kata Soegianto.
“Namun, saya terkadang menceritakan kepada pasien saya tentang tragedi yang saya alami, mereka tidak pernah mempermasalahkannya, tapi merekomendasikan terapi saya kepada teman-temannya,” ujarnya.
Rekonsiliasi menjadi semakin sulit
Soegianto dan Maridi merasa menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka ditangkap, disiksa dan ditahan selama lebih dari satu dekade atas tuduhan kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan, namun tanpa pengadilan. Di masa tuanya, mereka ingin namanya dikembalikan.
Namun, mereka tak mau mencari tahu siapa yang bersalah dan menuntut hukuman setimpal. Menurut mereka, proses peradilan dan pengungkapan kebenaran sulit dilakukan di Indonesia karena masing-masing pihak punya versi kebenarannya masing-masing.
Mereka hanya ingin negara membuka jalan rekonsiliasi melalui Nawacita – salah satunya komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM – agar mereka bisa segera melepaskan diri dari beban masa lalu. Keduanya berharap negara mengakui sejarah kelam tragedi ’65 serta para korban dan penyintas yang masih hidup.
“Semua pihak harus bisa saling menerima dan memaafkan tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa curiga terhadap saudara senegaranya, apalagi terhadap orang seperti kita yang tidak pernah terbukti bersalah,” kata Soegianto.
“Tidak ada lagi diskriminasi, berikan kami hak-hak kami sebagai warga negara lainnya tanpa membeda-bedakan,” tuntut Maridi.
Sayangnya, pengepungan LBH Jakarta pekan lalu kembali membangkitkan trauma para penyintas dan menggagalkan upaya bangsa Indonesia untuk berdamai dengan masa lalu. Menguatnya kembali sentimen antikomunis disertai intimidasi terhadap peristiwa terkait tragedi ’65 di berbagai daerah semakin menjauhkan Indonesia dari jalur rekonsiliasi.
“Sudah 52 tahun berlalu, tapi sepertinya rekonsiliasi semakin sulit,” kata Sugianto.—Rappler.com