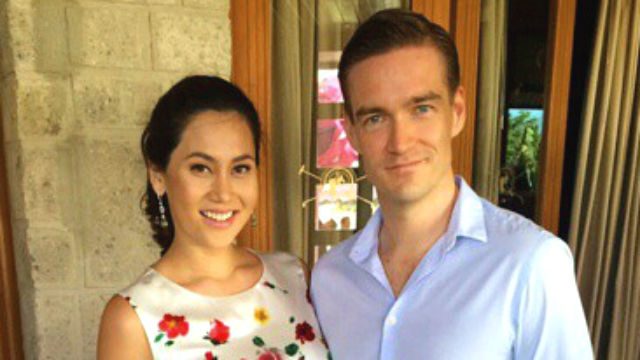Pendeta yang mencatat sejarah kaum ‘Kiri’ di Wonogiri
keren989
- 0
Kehilangan kata-kata di hadapan Luweng Mloko
Tanpa menabur bunga, saya rasa ziarah ini masih sah
38 tahun telah berlalu dan masih terlihat jelas
Rentetan tembakan dan teriakan mengiringi jatuhnya para tahanan
Terbentur dinding berbatu
Berbaring dalam kegelapan
Apakah Anda masih hidup, terluka atau mati tidak lagi menjadi masalah
Pesan teror jelas mengancam penduduk setempat
Jika sudah mencoba, berani bertanya kenapa
Barangkali pohon dadap berduri di pinggir Luweng bisa menjadi saksi
Seperti apa wajah ketiga truk yang ditangkap sebelum tewas
Benarkah mereka dengan gembira menyanyikan “Genjer-Genjer”, juga “Internasional”
Atau apakah Anda berdiri diam dalam ketakutan dalam perjalanan sepuluh kilometer dari kamp
Dengan ibu jari diborgol dan diikat ke belakang, matanya ditutup dengan kain hitam
Saat kematian dipaksakan, tak peduli hati menyerah atau memberontak karena penasaran
Tendangan Lars, peluru tet tet tet tet tet, mengambil alih otoritas malaikat maut
Di alam, penilaian terjadi dengan satu atau lain cara, saya tidak peduli
Namun yang jelas di sini adalah: impunitas
Kehilangan kata-kata di hadapan Luweng Mloko
Keheningan di sekitar perbukitan kapur tandus yang tandus bercerita banyak hal
Generasi demi generasi, satu demi satu
58 tahun Indonesiaku merayakan kemerdekaan
Dan masih banyak lagi cerita luweng mloko yang seperti ini;
Kesenjangan yang terus menerus tidak dapat ditutupi
Dan angin berkabut membawa bau gendruwo, mambang dan peri
Dan tanpa ada bunga yang bertebaran
Tulang belulangnya tersebar di perbukitan kapur Luweng
Mengadu dengan tenang dan sabar ke Komnas HAM
Menantikan kerja komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Memanggil umat manusia meminta makna pada Ibu Pertiwi
Puisi di atas merupakan karya Yahya Tirta Prewita, seorang pendeta, penyair, dan aktivis kemanusiaan yang tinggal di Purwantoro, ujung timur Kabupaten Wonogori, Jawa Tengah. Puisi tersebut dipersembahkan untuk JJ Kusni, seorang penulis sayap kiri yang menjadi pengasingan di Eropa pada masa Orde Baru.
Puisi yang ditulis pada Agustus 2003 itu diberi judul Luweng Mloko, yang berkisah tentang gua vertikal di kawasan perbukitan karst gersang yang menjadi saksi bisu penghilangan paksa ratusan orang yang diyakini simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada periode 1965-66. Ayat-ayat tersebut merupakan penggalan sejarah setengah abad lalu yang hampir terlupakan.
Yahya merupakan aktivis sosial yang membela kelompok marjinal, petani, dan korban peristiwa 1965. Lulusan teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta yang ditahbiskan menjadi imam sejak tahun 1992 ini memiliki catatan peristiwa berdarah “kelompok merah” di Wonogiri.
Di luar gereja dan jemaahnya, Yahya mendata dan menuliskan dalam catatan pribadinya kisah para saksi dan penyintas yang masih hidup. Ia berhasil menemukan sekitar 100 saksi dan penyintas di Wonogiri pada awal tahun 2000an, namun jumlahnya semakin berkurang setiap tahunnya karena banyaknya korban jiwa.
Wonogiri pernah menjadi tempat perlawanan anti-swapraja Tan Malaka terhadap Keraton Kasunanan Surakarta dan menjadi tempat pelarian tokoh komunis Amir Syarifuddin dan Muso pasca peristiwa Madiun tahun 1948. Pada pemilu tahun 1955, PKI meraih perolehan suara terbanyak kedua setelahnya. Partai Nasional Indonesia (PNI).
Gejolak politik tahun 1965 di ibu kota membawa dampak hingga ke daerah-daerah. Simpatisan PKI di Wonogiri diburu, ditangkap, ditahan, dan sebagian lainnya dieksekusi tanpa diadili. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) ’65 pernah memperkirakan sekitar 1.000 orang di Wonogiri dihilangkan secara paksa.
Yahya mengatakan tapol di Wonogiri mendapat stigma seumur hidup. Di Kabupaten Purwantoro misalnya, bagi mereka yang memiliki masa lalu sebagai penganut ideologi komunis, Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diberi tanda “ET” yang merupakan singkatan dari mantan tahanan politik (tapol).
Mereka juga selalu dijadikan kambing hitam ketika terjadi keresahan di masyarakat. Pada pemilu lalu sebelum Orde Baru tumbang, banyak terjadi kerusuhan kecil di Wonogiri, dan eks tapol ditangkap karena dianggap bertanggung jawab.
“Orang-orang yang sudah tua dipanggil dan dikumpulkan, diberi pelatihan, seolah-olah mereka adalah perusuh,” kata Yahya.
Peristiwa inilah yang kemudian menyulut simpati Yahya terhadap eks tapol dan keluarga korban 1965. Akal sehatnya merasakan ketidakadilan dan diskriminasi bahkan setelah pihak berwenang tega membiarkan ratusan ribu orang mati di tangan rakyatnya sendiri.
Yahya prihatin eks tapol ’65 dianggap sebagai orang terburuk di negara yang menganut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Suara mereka dibungkam, dan hak-hak mereka sebagai warga negara dibatasi karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijelaskan.
“Sebagai pemimpin jemaah, saya merasa memiliki kewajiban moral yang merupakan bagian dari kesalehan sosial atas nama kemanusiaan – untuk melayani mereka yang tertindas,” kata pendeta Gereja Kristen Jawa Purwantoro itu.
Tanpa melibatkan pihak gereja, ia bergerak sendiri mencari saksi-saksi yang tersebar di Wonogiri dan mencatat sejarah kisahnya agar tidak pernah mati. Ia menyadari bahwa hari demi hari semakin sedikit orang yang selamat dan menjadi saksi peristiwa ’65. Kalaupun masih ada, tidak mudah menemukan mereka yang ingatannya masih bagus karena rata-rata adalah orang lanjut usia di atas 70 tahun.
Ia pun memperjuangkan agar rekonsiliasi bisa terwujud. Menurut Yahya, rekonsiliasi hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian besar seperti Gus Dur. Beberapa bukti pelanggaran HAM dalam peristiwa ’65 sudah lebih dari cukup, termasuk rekomendasi terbaru Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag tahun lalu.
“Rekonsiliasi dimulai dengan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. “Pengakuan adalah ajaran teologis dasar semua agama,” ujarnya.
Kuburan massal dan penghilangan paksa
Yahya mencatat, ada 22 kuburan massal di Wonogiri yang merupakan tempat eksekusi terduga komunis. Beberapa saksi pun menceritakan kejadian berdarah tersebut.
Di Purwantoro, pada Desember 2002, ia menemukan dua saksi yang tersisa, Satiman dan Sodimeja, penggali kuburan massal Puh Doyong dan Sekar Sanan, dimana sekitar 130 orang tewas di tangan algojo. Dia dengan rapi menuliskan kesaksian mereka.
Satiman dan Sodimeja serta beberapa orang lainnya disuruh prajurit menyiapkan kuburan sedalam dada orang dewasa. Mereka tidak berani menanyakan apa dan siapa.
Mereka melihat tahanan itu diturunkan dari truk dengan pergelangan tangan dan kedua ibu jarinya terikat. Para penggali kubur kemudian diberitahu oleh tentara untuk menjauh, tapi mereka bisa mengawasi dari kejauhan.
Kemudian satu persatu para tawanan disuruh masuk ke dalam lubang galian tersebut. Ada sekelompok narapidana yang berpakaian rapi dan berpenampilan rapi, namun ada juga yang miskin, berambut gondrong, dan kurus.
Satu orang, satu lubang. Suara senjata dan pistol mengakhiri nyawa para tahanan satu per satu. Ada pula narapidana yang ditembak sebanyak tujuh kali namun terus mengeluarkan suara rintihan hingga akhirnya terkubur di dalam tanah.
Satu orang, satu lubang. Suara senjata dan pistol mengakhiri nyawa para tahanan satu per satu. Setelah eksekusi, para penggali kubur dipanggil untuk menutupi jenazah dengan tanah, tanpa upacara atau doa. Ada pula narapidana yang ditembak sebanyak tujuh kali namun terus mengeluarkan suara rintihan hingga akhirnya terkubur di dalam tanah.
Seorang tentara juga menasihati para penggali kubur untuk tutup mulut atas apa yang mereka saksikan. Jika ada yang mendengar suara pistol dan bertanya, disuruh berbohong bahwa ada tentara yang sedang berlatih menembak di kuburan.
Di sisi utara kuburan terjadi sedikit pembongkaran. Kemudian seekor anjing mencuri tengkorak manusia tersebut dan membawanya ke jalan utama.
Sayangnya, kedua saksi tersebut kini sudah meninggal. Namun cerita keberadaan kuburan massal ini dibenarkan oleh beberapa penyintas dan warga sekitar Purwantoro.
Amir Suripno, mantan pengurus YPKP ’65 yang kini tinggal di Wonogiri, mengaku tim YPKP asal Jakarta mendatangi makam tersebut untuk keperluan penelitian. Namun kuburan tersebut tidak mungkin dibongkar atau dipindahkan karena kini sudah ditimpa dan digunakan untuk kuburan baru, sedangkan sebagian lainnya sudah menjadi ladang dan sawah.
“Saya dengar ada sekitar 144 orang yang dimakamkan di sana. “Kuburannya ada di bawah, yang atas sekarang dijadikan kuburan umum,” kata Amir.
Selain kuburan massal di Wonogiri, Luweng Mloko juga sepi. Luweng yang dikunjungi Yahya bersama Amir pada tahun 2003, memang tidak setenar Luweng Grubug di Semanu, Gunung Kidul, gua vertikal yang terkenal dengan “cahaya surgawi” dan sungai bawah tanah yang kini menjadi tempat wisata goa.
Keduanya pernah menjadi tempat algojo mengeksekusi tahanan yang diduga komunis.
Kisah Luweng Grubug pernah diceritakan oleh Pastor Paul de Blot, seorang pastor, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) saat itu yang menyaksikan eksekusi di lubang kematian.
Sementara itu, Luweng Mloko di Johonut, Paranggupito, mungkin hanya diketahui warga lanjut usia setempat, seperti Pak Paimo yang menyaksikan eksekusi pada Jumat malam Pon. Sehari sebelumnya ada perintah dari kepala desa untuk membuat jalan menuju ke Luweng, namun tidak dijelaskan tujuannya.
Sore harinya, Paimo diperintahkan tentara untuk berjaga di bukit lain pada tengah malam untuk mencegah pedagang yang berjalan menuju pasar mendekati lokasi Luweng. Tiga truk tentara berhenti di pertigaan dekat bukit. Beberapa saat kemudian, serangkaian suara tembakan terdengar menembus malam.
Beberapa hari kemudian, bau bangkai menyebar. Seluruh warga dikerahkan untuk menutupi luweng dengan dedaunan. Ada sesosok mayat dengan sarung menempel di pinggir gua, Paimo dan warga mendorongnya dengan bambu hingga terjatuh ke dasar. Selama berbulan-bulan, angin membawa bau bangkai ke kota-kota sekitarnya. —Rappler.com
BACA JUGA: