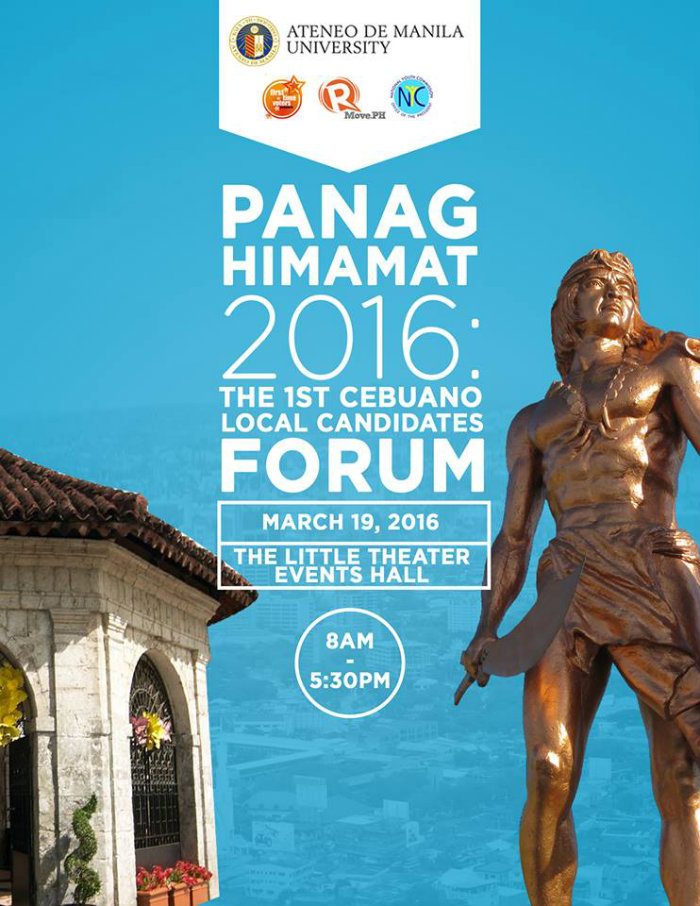Surat Guru dari Pulau Buru
keren989
- 0
Oktober 1965, suatu sore, saya bertemu tiga orang untuk menyampaikan kabar bahwa saya dipanggil Bupati Citro untuk datang ke kecamatan. Tidak perlu membawa apa-apa, katanya hanya sebentar.
Saya pikir ada sesuatu yang penting. Saya kebetulan kenal dengan Camat Purwantoro. Saya meninggalkan putri saya dan kemudian pergi ke kecamatan. Ada 11 orang disana, sebagian besar saya kenal, ada juga guru seperti saya.
Saya kepala sekolah SD Gondang, sebuah sekolah negeri yang terletak tidak jauh dari rumah saya. Saya juga aktif di organisasi profesi dan pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Indonesia Non-Vaksentral (PGRI) Purwantoro.
“Tenang, tidak usah khawatir, tidak apa-apa,” kata Camat Citro mencoba menenangkan kepanikan kami saat mobil tentara datang di tengah kegelapan.
Kami diangkut ke Wonogiri, pusat kabupaten yang berjarak sekitar 60 kilometer dari tempat tinggal saya. Sesampainya di kota, mobil berhenti di depan kantor militer. Seorang petugas berteriak: “Bawa saja dia langsung ke penjara!” dia memerintahkan.
Kelompok kami segera dibawa ke penjara di kota. Saya beruntung tidak ditampar oleh tentara yang memimpin kami. Saya melihat beberapa teman saya dipukuli dan ditendang sebelum dimasukkan ke dalam sel.
Teror penjara kota
Ponselku sebenarnya untuk 7 orang, tapi 37 orang, jadi ramai. Narapidana hanya bisa berdiri berdesakan, tidak bisa duduk, pengap dan panas. Yang lebih menakutkan lagi adalah sel di sebelah saya, ukurannya sedikit lebih besar, namun dapat menampung 80 orang.
Makanan kami hanya sejumput nasi jagung atau segenggam nasi dalam kaleng yang ditaruh di bawah panggangan besi.
Teror paling mengerikan terjadi hampir setiap hari – “night bon”. Orang-orang yang “terikat” itu dijemput dengan truk, dibawa pergi, namun tidak pernah kembali ke penjara, entah menghilang kemana.
Bunyi kunci sel dan derit pintu besi di malam hari membuat kami bergidik. Tidak ada suara, tidak ada yang berani berbicara. Dengan jantung berdebar kencang, kami menunggu siapa yang akan dipanggil malam ini.
Saya hampir “hilang” suatu malam. Tapi apapun yang terjadi, aku masih hidup.
“Sudarsono, pimpinan SD Gondang sudah keluar!” teriak petugas itu setengah berteriak.
“Diam saja, jangan keluar. “Kalau kamu bertanya, itu bukan namamu,” bisik teman-temanku.
Nama saya Darsono, bukan Sudarsono. Aku hanya diam, menuruti apa yang mereka katakan.
Prajurit itu mengulangi panggilan itu tiga kali. Saya tidak bergerak. Saya tidak tahu apa yang membuatnya pergi. Petugas mungkin berasumsi bahwa narapidana tersebut tidak ada, atau “diikat” pada malam sebelumnya, namun namanya tidak dicoret. Yang jelas saya lolos dari kematian.
Setiap malam satu atau dua orang diambil dari setiap sel. Di sel tempatku berada, hanya tersisa 6 orang. Saya tinggal di Lapas Wonogiri selama enam minggu sebelum menjalani interogasi.
“Adik Ketua PGRI Purwantoro?” tanya petugas di kantor kejaksaan.
“Benar. Saya guru, organisasinya PGRI,” jawab saya.
“Apakah kamu pernah mengadakan 120 pertemuan gelap?” dia bersikeras.
“Tidak pernah,” kataku.
“Pernah ngobrol di komunitas?” Tanyakan dia
“Sering, tapi selalu di depan camat, polisi, dan TNI. “Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada pertemuan rahasia,” jawab saya meyakinkan sambil menyebutkan nama pejabat pemerintah, polisi, dan militer yang mendengarkan ceramah saya.
Petugas kejaksaan kemudian menunjukkan surat yang mengabarkan bahwa saya sering mengumpulkan orang dalam pertemuan yang gelap. Namun, saya tetap menyangkalnya.
Kelaparan di Nusakambangan
Saya akhirnya dibawa ke Cilacap, ke Pulau Nusakambangan. Awal tahun 1966 saya masuk Lapas Permisan. Tidak ada penyiksaan fisik atau “bon-bonan” di sini, tapi setiap hari saya menyaksikan kengerian lainnya. Mayat-mayat tergeletak berserakan, satu demi satu narapidana mati kelaparan di penjara.
Setiap orang hanya boleh makan satu bongkah singkong setiap kali makan – hanya tiga bongkah per hari. Kondisi para narapidana yang masih hidup juga sangat memprihatinkan, hanya tersisa tulang dan kulit seperti mayat hidup.
Tubuh tidak memiliki energi. Saya masih ingat, untuk berdiri saya harus menyangga kedua tangan di dinding dan bergerak sangat pelan seperti orang tua.
Sekitar enam bulan kemudian tahanan tersebut mulai merasa sakit. Mereka tewas dan tergeletak di lantai sel yang dingin. Ada 27 narapidana di sel tempat saya berada yang meninggal secara bergantian, dua di antaranya adalah aparat desa di Purwantoro. Terkadang tiga orang meninggal dalam sehari karena penyakit dan kelaparan.
Anehnya, kami tega untuk tidak melaporkan kematian teman satu sel tersebut. Kami membaringkan orang mati di pojok belakang seolah-olah mereka sedang tidur untuk mengelabui para sipir, padahal ada yang curiga karena kami selalu menemukan mereka tertidur sepanjang hari.
“Kenapa di belakang?” tanya petugas penjara.
“Tidur pak, katanya seharian tenggelam,” ajak kami.
Dengan demikian, mereka yang meninggal tetap mendapat jatah makanan. Kami kemudian membagi jatah makanan secara merata kepada para tahanan yang masih hidup sehingga mereka bisa makan lebih banyak.
Baru setelah tiga atau empat hari kami melaporkan kematian mereka dan mengeluarkan jenazahnya.
Saya diselamatkan oleh keluarga saya di rumah. Suatu hari mereka mengirimi saya banyak makanan dan pakaian. Nikmatnya makan nasi, sambal, dan ikan asin saja bisa saya rasakan.
Lalu saya membagikan makanan dan pakaian kepada sipir penjara, Dulah, seorang narapidana kriminal berat yang paling ditakuti di Permisan. Sejak saat itu dia bersikap ramah dan sering mengeluarkan saya dari sel, bahkan penjaga penjara pun tidak berani menghentikannya.
“Saya ingin mengeluarkan Darsono agar dia bisa bekerja di kebun,” kata Dulah kepada petugas penjara.
Saya sangat beruntung, akhirnya menjadi tahanan luar setelah enam bulan di dalam sel. Mandor pun mengizinkan saya mengajak dua orang untuk menemani saya bekerja di kebun.
Kami bertiga mendirikan gubuk untuk tidur di luar penjara. Saya memelihara kambing, kebun, dan ikan setiap hari. Terkadang saya juga mencari katak hijau besar untuk dimakan.
Saya menanam apa saja yang bisa dimakan di kebun, seperti pisang, singkong, dan tomat. Saya bebas makan di luar, sehingga tubuh saya secara bertahap mulai pulih ke keadaan semula.
Tapi saya membayangkan nasib para tahanan di dalam, yang jumlahnya semakin berkurang dari hari ke hari. Ketika para penjaga tidak sadar, saya juga menyelundupkan makanan ke penjara untuk para tahanan. Saya telah melakukan ini berkali-kali dan tidak pernah menangkapnya.
Saya mengelola kebun dan sawah di luar penjara dengan bantuan teman-teman saya. Tanah Nusakambangan subur dan hasil panennya melimpah. Saya biasa mematangkan 50 hingga 70 tandan pisang sekaligus, lebih dari cukup untuk mengisi perut para tahanan. Bahkan saya sendiri yang mengirimkan pisang dan singkong dari kebun kepada petugas lapas agar mereka selalu datang ke gubuk tempat saya tinggal untuk meminta makanan.
“Sudah cukup, jangan kirimi aku makanan lagi,” aku menulis surat kepada keluargaku di kampung halaman.
Tujuan suratku bukan untuk memberatkan istri dan anak-anakku, namun mereka mengira aku akan mati di penjara karena menolak kiriman tersebut. Keluargaku bahkan mengadakan perayaan.
Saya bertahan di Nusakambangan selama sepuluh tahun sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Buru pada tahun 1975 dengan kapal ternak yang membawa sekitar 400 orang tawanan. Bau limbah dan derasnya ombak Samudera Hindia di malam hari membuat para narapidana mabuk laut.
Kapal berlabuh di Pulau Buru setelah tujuh hari berlayar. Sore harinya kami terpaksa berjalan lebih jauh menuju kamp penahanan yang jaraknya sekitar 30 kilometer. Saya melihat ada yang terjatuh karena kelelahan, tentara yang mengawal kami langsung menendangnya dari belakang. Tidak bisa berhenti.
Bertemanlah dengan Pramoedya
Untungnya, kami bukan orang pertama yang dikirim ke sini. Jadi kami disambut oleh para tahanan yang lebih dulu datang ke sini. Kebanyakan orang Jawa, dan kami berbicara bahasa Jawa agar tidak dimengerti oleh tentara yang sebagian besar adalah orang Indonesia Timur.
Di sini para tapol saling memanggil “lur” dari kata “sedulur” yang berarti saudara.
“Ada apa dengan Lur, ada apa dengan Java? (Bagaimana keadaan Java sekarang)? kata tahanan yang menetap di sini.
Di sinilah pula saya berteman dengan Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis Indonesia yang juga ditangkap Orde Baru.
Di mata saya, Pram adalah orang yang sangat sabar dan tidak bisa ditekan. Pram pernah diteriaki tentara dan diancam akan dipukuli, namun ia tidak pernah takut.
Pukul saja dia kalau tega, kata Pram santai.
Dia bisa melindungi seluruh tahanan di Pulau Buru. Meski berbeda satuan, kami sering bertemu dan ngobrol. Saya di unit S, sedangkan Pram di unit pusat.
“Bagaimana Dar, bagaimana kabar teman-teman satu unitmu, apakah semuanya baik-baik saja?” Kalimat itulah yang biasa ditanyakan Pram kepada saya.
Kehidupan di Pulau Buru lebih baik dibandingkan di penjara Nusakambangan yang kelaparan. Di sini kami tinggal di barak dan setiap hari menebangi hutan untuk dijadikan sawah dan ladang.
Orang Jawa dari desa seperti saya kebanyakan mempunyai keterampilan bertani padi. Meskipun saya seorang guru, saya juga memiliki dan menggarap sawah di Purwantoro sebelum saya ditangkap.
Kami dorong 70 hektar sawah, 30 hektar perkebunan jagung, ubi jalar, kelapa, dan pisang. Sapi yang awalnya diberi 50 ekor sapi per unit, dalam waktu tiga tahun melahirkan 200 ekor sapi. Ada yang disembelih, ada pula yang untuk membajak sawah. Kami juga mengajari penduduk asli makan nasi.
“Ini rumah kita Lur, kita tidak akan pernah kembali ke Jawa lagi,” canda teman-temanku.
Pulau Buru, dari hutan belantara, menjadi gudang makanan para tahanan politik. Namun, aku tetap merindukan keluargaku, anak-anakku yang tinggal bersamaku ketika mereka masih kecil.
Suratku dari Pulau Buru
Segala kisahku kutulis selama aku berada di penjara kota, Nusakambangan, hingga aku dibuang ke Pulau Buru. Saya mengumumkan hal ini melalui surat kepada keluarga saya, dan saya katakan kepada mereka bahwa saya sangat ingin pulang, bebas memilih tempat tinggal di negara ini.
Pada tahun 1979 tersiar kabar bahwa kami akan dibebaskan. Saya akan membagikan kabar gembira ini kepada keluarga saya. Tak lama kemudian, berita tersebut menjadi kenyataan. Kami diangkut dengan KRI Dewaruci dan kembali ke Pulau Jawa.
Kapal sandar di Tanjung Mas Semarang. Saya diundang oleh keluarga saya. Mereka tidak mengenalku, tapi aku mengenal mereka. Anak-anak saya sudah dewasa. Kami menangis bersama.
Ketika saya kembali ke Purwantoro, saya takut orang-orang akan membenci atau memusuhi saya karena saya adalah mantan tahanan politik yang diyakini terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tapi tebakanku salah total. Penduduk desa mengunjungi rumah saya ingin bertemu dan bertanya tentang berita. Mereka membawakanku makanan. Warga juga bergotong royong memperbaiki rumah saya yang hampir roboh, ada pula yang mencangkul ladang saya agar bisa ditanami.
Selama sebulan rumahku dijaga setiap malam. Aku merasa beruntung, mereka tidak menganggapku sebagai pengkhianat dan perusuh. Mereka tahu bahwa saya adalah guru anak-anak mereka.
Pejabat kota saya juga memihak saya. Mereka mencabut Kartu Tanda Penduduk (NID) saya tidak lama setelah saya sampai di rumah, lalu memperbaruinya dengan menghapus label ET (ex-tapol).
Tidak lama setelah itu, seorang guru muda yang saya kenal datang ke rumah saya. Dia memohon maaf kepada saya karena telah membuat surat laporan palsu sehingga membuat saya menjadi tahanan selama lebih dari 13 tahun. —Rappler.com
Darsono (86 tahun) adalah mantan guru yang merupakan tahanan politik, penyintas penangkapan dan penghilangan paksa pada tahun 1965-66, yang kini tinggal di Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Ia berbagi pengalamannya dengan Rappler untuk mengungkap kebenaran yang selama ini dirahasiakan.
BACA JUGA: